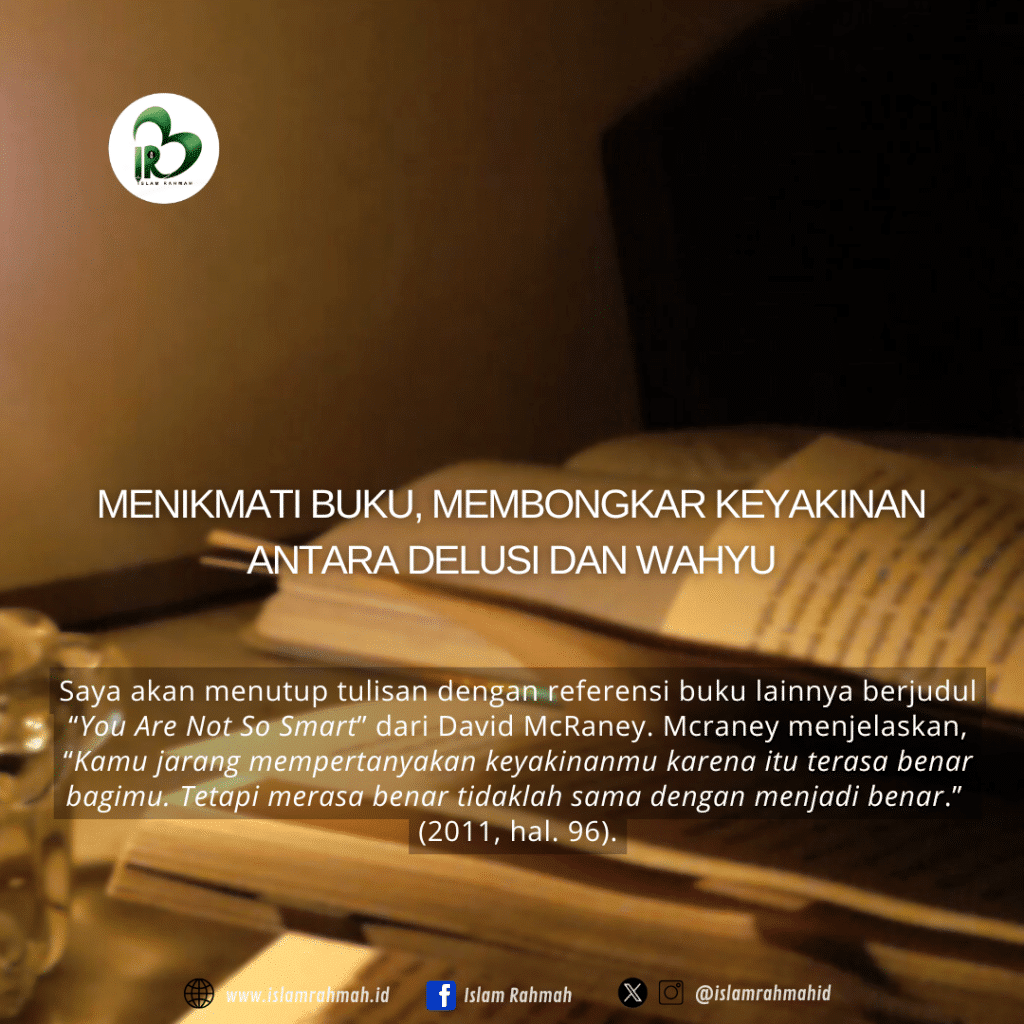
Menikmati Buku, Membongkar Keyakinan antara Delusi dan Wahyu
“Salah satu cara yang dapat diandalkan untuk membuat orang percaya pada kepalsuan adalah dengan mengulanginya secara sering, karena sesuatu yang familiar sulit dibedakan dari kebenaran.” – Daniel Kahneman.
Ramadan bersama buku membawa saya pada kutipan di atas, dari buku berjudul “Thinking, Fast and Slow” karya Daniel Kahneman (2011) pada halaman 62. Buku ini secara keilmuan mengupas tentang bias konfirmasi sebagai kecenderungan manusia untuk mencari, menafsirkan, dan mengingat informasi yang mendukung keyakinannya.
Bukan tanpa alasan buku ini kembali saya ulang baca di subuh hari, setelah sebelumnya seorang kawan berkeluh kesah karena lapak jualannya belakangan sepi. Namun, ia mengaitkannya dengan sebuah ‘keyakinan’: “istriku sering nyapu rumah malam-malam.”
Sedikit cerita yang pernah saya dengar, di kalangan masyarakat Sunda, ada kepercayaan bahwa menyapu rumah di malam hari akan membuang rezeki. Bagi saya jelas tahayul. Tapi sayangnya, lebih banyak yang yakin.
Perjalanan Mencerna Nasihat
Setelah mendengar ‘cerita menghibur’ dari kawan tadi, ingatan saya sejenak melonjak ke perjalanan menyusun Buku Sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (1925-2025). Dalam sebuah dokumen yang kami kompilasi menjadi buku, ada sebuah catatan yang sangat menarik – dan PENTING.
Sebuah sebuah sesi Mulaqat Majelis Amillah Nasional JAI dengan Hadhrat Khalifatul Masih V atba. pada 30 September 2013 bertempat di Masjid Thaha, Singapura, Yang Mulia Hudhur memberikan arahan, Buku Haqiqatul Wahy harus diterjemahkan, karena banyak masyarakat Indonesia yang masih kurang pendidikan, sehingga masih percaya pada magic, voodoo, dll, sehingga mudah-mudahan buku Haqiqatul Wahy dapat menjawab/memberikan pemahaman kepada banyak masyarakat anda.
Menarik. Karena Khalifah tercinta juga sangat paham dengan fenomena pemuja takhayul, klenik dan semacamnya yang masih beterbaran di sekitar kita. Seperti halnya cerita kawan saya di atas, di balik ketidaktahuan kadang harapan justru bercampur dengan kelucuan.
Dalam pusaran keyakinan, batas antara keyakinan sejati dan delusi kerap mengabur – sekaligus menghibur. Seorang pedagang yang rugi mengklaim segalanya disebabkan kebiasaan menyapu malam hari. Seorang pemimpin yang haus kuasa juga kerap menyandarkan legitimasinya pada bisikan gaib atau jimat. Alhasil, tersebarlah kisah-kisah yang merayakan ilusi seolah kebenaran mutlak.
Buku Haqiqatul Wahy menyoroti fenomena ini dengan tajam. Dalam catatannya, Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as. membedakan dengan jelas antara wahyu sejati dan pikiran manusia yang terjebak dalam ilusinya sendiri. Beliau as. menyatakan bahwa tidak semua yang dikira wahyu atau ilham berasal dari Tuhan.
Banyak yang hanya refleksi dari kecemasan dan ambisi pribadi, tetapi diterima tanpa penyaringan kritis. “Setan adalah musuh yang nyata bagi manusia,” mengingatkan bahwa wahyu sejati tidak bisa disandarkan pada anggapan pribadi belaka.
Dalam buku ini, dikatakan bahwa ada orang yang menerima mimpi yang benar, tetapi bukan karena mereka orang suci atau terpilih. Bahkan seorang pencuri, pezina, atau seorang yang terperosok dalam lumpur syirik bisa saja mengalami mimpi yang seolah menjadi kenyataan. Lantas, apakah mimpi mereka bisa dijadikan dasar sebuah keyakinan? Ataukah sekadar kebetulan yang dikultuskan?
Di bagian lain, buku ini juga menyinggung bahwa wahyu yang sejati tidak pernah sekadar membenarkan kepentingan pribadi. Wahyu tidak lahir dari ego, tetapi dari hubungan mendalam dengan Yang Maha Kuasa.
Fenomena penyalahgunaan ilham dan wahyu ini terus berulang dalam berbagai wajah zaman. Di tengah derasnya arus informasi, kita masih menemukan individu yang mengaku mendapat “penglihatan” tentang masa depan. Dalam kepala yang enggan berpikir kritis, kepercayaan seperti ini akan menyuburkan manipulasi.
Maka, seperti yang dikatakan dalam buku ini, yang dibutuhkan bukan sekadar iman, tetapi juga kejernihan akal. Antara wahyu dan delusi, ada garis yang harus ditelusuri dengan hati-hati.
Mengapa Takhayul Begitu Meyakinkan?
Di sinilah letak bahaya terbesar dari takhayul, yaitu ketika seseorang meyakini mimpi atau firasatnya sebagai kebenaran mutlak tanpa mengujinya dengan akal dan bukti nyata. Ia bisa saja merasa bahwa setiap perasaan yang menggetarkan jiwanya adalah pesan dari langit, padahal mungkin itu hanya refleksi dari pikirannya sendiri.
Pertanyaan sederhana, memangnya sudah sedekat apa kita dengan Tuhan?
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad as. dalam buku ini seakan memberi peringatan: tidak semua yang tampak spiritual adalah wahyu, dan tidak semua yang terlintas dalam benak adalah kebenaran. Tanpa penyaringan akal dan kejelasan hati, seseorang bisa jatuh ke dalam fanatisme yang membutakan.
Kita tidak dilarang percaya pada pengalaman spiritual, tetapi jangan sampai membawa kita pada jebakan kesalehan. Haqiqatul Wahy bukan sekadar buku tentang wahyu, tetapi juga sebuah refleksi tentang bagaimana manusia seharusnya menyikapi kepercayaan dengan cermat, menghindari jebakan takhayul, dan membedakan antara tuntunan Tuhan dan sekadar bayang-bayang pikiran.
Dalam psikologi evolusioner, kepercayaan pada takhayul dijelaskan sebagai mekanisme bertahan hidup. Pada masa manusia purba, mereka mengasosiasikan suara gemerisik di semak-semak dengan kehadiran predator. Meskipun suara itu bisa saja hanya disebabkan oleh angin, insting untuk menghubungkannya dengan bahaya membantu nenek moyang kita menghindari risiko.
Di dunia modern, seseorang yang haus kekuasaan bisa saja mengatakan, “Saya bermimpi, Tuan Fulan memberikan sebuah tongkat dan memakaikan saya jubah,” yang kemudian diartikan bahwa ia adalah orang yang harus melanjutkan estafet kepemimpinan.
Kepercayaan terhadap takhayul sering kali berakar pada bias kognitif, terutama confirmation bias (bias konfirmasi) dan illusory correlation (korelasi ilusif). Confirmation bias terjadi ketika seseorang hanya mencari dan mengingat kejadian yang mendukung keyakinannya, sambil mengabaikan bukti-bukti yang bertentangan. Misalnya, seorang pedagang yang percaya bahwa burung gagak adalah pembawa sial, akan lebih mudah mengingat hari-hari buruk yang diawali dengan melihat burung tersebut, dan mengabaikan hari-hari biasa di mana burung gagak juga hadir tetapi bisnisnya tetap lancar.
Sementara itu, illusory correlation adalah kecenderungan manusia untuk melihat hubungan sebab-akibat antara dua hal yang sebenarnya tidak memiliki keterkaitan. Misalnya, pelanggan pertamanya di pagi hari membayar dengan uang kertas yang kusut, lalu dagangannya sepi—ia seketika menganggap uang kusut sebagai “pertanda buruk.” Padahal kondisi pasar, daya beli masyarakat, cuaca, atau faktor lain juga memengaruhi naik-turunnya penjualan.
Sayangnya, mekanisme ini bertahan hingga sekarang dalam bentuk kepercayaan pada pertanda-pertanda yang tidak berdasar. Pola pikir seperti ini berkembang karena manusia secara alami cenderung mencari keteraturan dalam ketidakpastian, meskipun keteraturan itu sebenarnya tidak nyata.
Saya akan menutup tulisan dengan referensi buku lainnya berjudul “You Are Not So Smart” dari David McRaney. Mcraney menjelaskan, “Kamu jarang mempertanyakan keyakinanmu karena itu terasa benar bagimu. Tetapi merasa benar tidaklah sama dengan menjadi benar.” – (2011, hal. 96).
Views: 133

Masyaallah keren